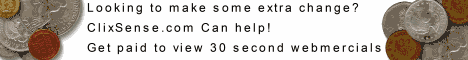Siapapun yang menjadi saksi hidup tsunami, pasti menyimpan ketakutan atas kejadian yang menelan korban ratusan ribu jiwa itu. Anehnya, justru kebanyakan memilih tinggal di tempat yang sama ketika mimpi buruk itu menyapa mereka.
Siapapun yang menjadi saksi hidup tsunami, pasti menyimpan ketakutan atas kejadian yang menelan korban ratusan ribu jiwa itu. Anehnya, justru kebanyakan memilih tinggal di tempat yang sama ketika mimpi buruk itu menyapa mereka.
Matahari masih belum lama bersinar, 26 Desember 2004 lalu. Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pun kebanyakan masih belum banyak yang meninggalkan rumah untuk memulai aktivitasnya. Tiba-tiba, bumi gerah dan mulai bergoyang. Menggoyang apapun yang ada di permukaan tanah. Pohon, bangunan, manusia hingga ternak ikut bergetar.
Penduduk bumi Serambi Mekkah yang sadar akan adanya gempa, memilih untuk keluar rumah. Warga yang tinggal di sekitar pantai melihat laut yang tiba-tiba surut, berselimutkan air menghitam di tengah laut. Teriakan mulai terdengar. “Air datang,...air datang,..” teriak orang-orang ketika itu. Kekacauan di pemukiman sekitar pantai tidak terhindarkan. Orang-orang berlarian ke jalanan. Gelombang semakin dekat dan menghempas apapun di sekitarnya.
Termasuk Nurmala, penduduk Desa Lam Geueu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar yang berjarak 3 Km dari Pantai Ujung Pancu, Peukan Bada. Perempuan yang ketika itu berlari menuju jalan besar bersama suaminya, Nurdin dan dua anaknya Heri dan Risky itu terjengkang ditabrak gelombang air yang tiba-tiba datang ke desanya. Ia bergulung-gulung di jalanan. Dua anak yang ada didekapannya pun lepas entah kemana.
Beruntung, di tengah-tengah gulungan air bercampur barang-barang itu, Nurmala sempat berpegangan di dahan pohon Asam Jawa yang ada di sebelah kanannya. “Untuk beberapa saat, saya ikut saja kemana pohon itu hanyut, yang penting selamat dahulu,” kata Nurmala. Air mengombang-ambingkan dirinya. Sampai kemudian air mendadak tenang, dan surut. Nurmala pun berhasil selamat. “Alhamdulillah, tak lama kemudian saya bertemu dengan seluruh keluarga saya yang juga selamat,” katanya.
Mimpi buruk itu tidak hanya datang saat gelombang menerjang. Usai tsunami, Peukan Bada bagai kota mati. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah, kecuali sebuah masjid bernama Maharaja Ghurah, dan sebuah bangunan rumah. Selebihnya puing-puing, rongsokan mobil, pohon-pohon yang tercerabut dari tanah hingga tiang listrik. Di sela-selanya, mayat manusia bergelimpangan.
Di Desa Meunasah Masjid, Leupung, Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pun terlebih lagi. Ketika gelombang tsunami terjadi, masyarakat di Desa Mamplam, Desa Meunasah Bak U, Desa Meunasah Masjid, Desa Lam Senia, Desa Pulot hingga Desa Layen harus berjibaku dengan gelombang ganas yang datang dari arah laut.
Jarak dari pantai yang dekat, membuat penduduk tidak punya waktu banyak untuk menyelamatkan. Ribuan orang yang ada di desa ketika itu terseret arus hingga ke jajaran bukit yang ada di belakang desa. Melewati perkebunan dan sawah. “Banyak jenazah penduduk desa yang terseret sampai ke atas bukit sana, menandakan betapa hebat kejadian itu,” kaya Abdul Djalil, Sekretaris Desa Meunasah Masjid.
Lain lagi dengan Eliana, penduduk Naga Umbang Lhok Nga yang berjarak sekitar 5 Km dari bibir pantai ini tidak menyangka gelombang tsunami bisa sampai di kawasan tempat tinggalnya. Apalagi, kawasan tempat tinggal ibu satu anak ini terletak di kaki perbukitan Lhok Nga, Aceh Besar. Namun belum habis keheranannya, didapati kenyataan ayahnya meninggal dunia terseret arus.
Eliana menceritakan, ketika air datang, sang ayah adalah orang terakhir yang keluar dari rumah karena ingin menyelamatkan keponanannya. “Ayah saya tidak bisa menjangkau atap rumah tetangga, padahal seluruh keluarga sudah berada di sana, ayah pun meninggal dunia terseret air,” kenangnya.
Seperti Nurmala, Abdul Djalil, Eliana atau siapapun yang menjadi saksi hidup tsunami NAD-Nias pasti menyimpan ketakutan atas kejadian yang menelan korban ratusan ribu jiwa itu. Bahkan ketika Nurmala menceritakan kembali kejadian itu, kata-katanya tersendat. Meski diselingi tawa kecil. Seperti tidak mempercayai mukzizat hidup yang membuatnya tetap bernapas hingga hari ini.

Namun, ketakutan itu tidak berarti membuat mereka berpindah dari kawasan lama tempat tinggal mereka. Nurmala, Abdul Djalil, Eliana misalnya, tetap memilih berada di desanya. Pekerjaan sebagai nelayan dan kewajiban menjaga desa leluhur, menjadi alasan. Apalagi dalam perkembangannya, pindah tempat tinggal sama halnya berhadapan dengan berbagai “ketidakjelasan” baru. Terutama, “ketidakjelasan” mendapatkan rumah baru.
Keengganan pindah atau relokasi ke tempat baru, di satu sisi membuat upaya pembangunan kembali kawasan lama memerlukan energi ekstra. Hal itu dikatakan oleh House Officer Plan Aceh, Onny Trijunianto. Menurutnya, membersihkan lahan dan menata kembali, perlu langkah-langkah yang tidak gampang. Untuk membangun 61 rumah dari 137 rumah (dibagi dengan ADB) misalnya, Plan Aceh berkonstrasi penuh pada village planning.
“Village planning penting untuk menata dan membangun kembali kawasan yang terkena bencana dengan prinsip militasi kawasan bencana, sekaligus mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Onny. Village planning untuk lahan seluas 8 Ha itu dimulai dari proses pemetaan tanah. Proses ini dilakukan warga secara partisipatif dengan out put kapling milik warga dan fasilitas desa.
Setelah itu, hasil pemetaan disosialisasikan kepada warga, sekaligus melakukan analisis penggunaan lahan, termasuk kemungkinan bencana terulang. Draft rencana didapat meleluai diskusi dengan masyarakat. Di dalamnya termasuk membicarakan rencana struktur ruang, rencana pemanfaatan ruang, sistem jaringan utititas seperti air, telepon, listrik, air limbang dan pengelolaan sampah. Rencana kepadatan bangunan dan ketinggian bangunan, tidak ketinggalan untuk dibicarakan. “Semua persiapan teknis itu setidaknya memerlukan waktu satu tahun,” kenang Onny.
Hal terpenting dari semua proses itu adalah upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih aman dari bencana. Meskipun pilihan yang terbaik untuk itu adalah relokasi, namun faktanya tidak memungkinan untuk itu. Di lokasi lama itu setidaknya memiliki perlindungan alami maupun bangunan dari gelombang tsunami. “Di dalamnya ada jalur penyelamatan dan tempat aman untuk penyelamatan, termpatnya bisa dibukit-bukit,” katanya.
Onny sadar, tidak semua elemen bisa bisa terpenuhi. Dengan “bahan baku” yang ada itulah, akhirnya diputuskan untuk membangun rumah tipe 36, seperti yang disyaratkan BRR kepada NGO yang akan ikut membantu membangun rumah. Sialnya, hasil pemetaan dan diskusi dengan masyarakat menghasilkan kesimpulan, masyarakat ingin rumah rekonstruksi mereka dibangun tepat di atas rumah mereka yang lama. Hasilnya, rumah baru itu pun tidak bisa tertata rapi.

“Kalau dilihat, rumah di Meunasah Masjid, Leupung terkesan kacau dan tidak tertata, hal itu karena rumah baru dibangun tepat di atas rumah lama,” katanya. Ujung dari hal itu adalah tidak sesuainya “ukuran” modern yang lebih baik. Termasuk adanya bengunan yang child friendly (ramah anak). Seperti tidak adanya ruang yang membuat anak bisa berbas bergerak untuk bermain. Sebagian besar, sempit dan berhimpitan.
Terlebih, adanya ruang anak-anak yang terdiri dalam ruang aktif (ruang terbuka untuk bermain) dan ruang pasif (kawasan untuk duduk-duduk, berinteraksi dengan bercerita dll), dengan dikelilingi tanaman yang mengililingi ruang anak-anak itu. “Bagaimana bisa ada, penataannya seperti desa Meunasah Lama sebelum tsunami,” kata Onny.