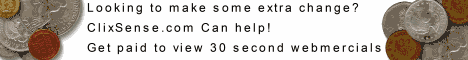Meski hanya sesaat, debu yang beterbangan usai dam truk melintas di jalan darurat menuju Desa Meunasah Masjid, membuat jalan itu tak layak lagi dilewati. Butiran kecil kecoklatan itu membuat gelap suasana. Di balik pekatnya debu di jalanan itulah, rumah relokasi Leupung berada. Rumah yang menjadi sadaran hidup korban tsunami.
Meski hanya sesaat, debu yang beterbangan usai dam truk melintas di jalan darurat menuju Desa Meunasah Masjid, membuat jalan itu tak layak lagi dilewati. Butiran kecil kecoklatan itu membuat gelap suasana. Di balik pekatnya debu di jalanan itulah, rumah relokasi Leupung berada. Rumah yang menjadi sadaran hidup korban tsunami.Jemari Zuhra menari di antara dan barang dagangannya. Sesekali, mulutnya meniupi debu-debu yang menempel di etelase kaca kiosnya. Setiap hari, tak terhitung lagi berapa kali perempuan beranak dua itu harus membersihkan debu dari barang dagangan yang di jual di kios jajanan dan voucer pulsa isi ulang tepi jalan Desa Meunasah Masjid. Di samping Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Leupung. “Debu di sini banyak sekali,” kata Zahra.
Zuhra adalah salah satu penghuni rumah rekonstruksi di Desa Meunasah Masjid, Leupung. Bersama Elma Purwani dan suami barunya, perempuan berusia 47 tahun itu menempati rumah yang dibangun oleh Plan Aceh. Ketika tsunami menerjang, 10 orang anggota keluarga Zuhra meninggal dunia atau hilang entah kemana. “Saya memutuskan untuk tetap tinggal di sini, karena inilah tempat tinggal kami,” kata Zahra.
Kecamatan Leupung, tepatnya di Desa Maunasah Masjid adalah salah satu daerah parah ketika tsunami menerjang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)-Nias, 26 Desember 2004 lalu. Dari seluruh Kecamatan Leupung yang memiliki populasi sekitar 10 ribu jiwa, yang selamat hanya sekitar 700-an orang. Di Desa Meunasah Masjid, hanya puluhan yang tersisa.
Meskipun letaknya hanya 15 Km dari Ibu Kota NAD Banda Aceh, namun tidak gampang menuju daerah ini. Terutama ketika melewati jalan darurat yang dibangun di atas lahan perkebunan yang penuh debu, terjal dan bergelombang. Kendaraan roda empat yang melintasi jalan itu, membuat debu itu menari-nari menutupi pandangan. Penduduk bersepeda motor, mau tidak mau harus berhenti sejenak untuk membiarkan debu-debu itu pergi tertiup angin.
Kehidupan di Desa Maunasah Masjid, Leupung mulai menggeliat. Rumah-rumah yang dibangun berbagai NGO seperti Plan Aceh, Muslim Aid, Habitat Humanity, Oxfam sejumlah 97 unit mulai ditempati. Sementara 85 unit milik Asean Development Bank (ADB) belum usai dibangun. Rencananya, rumah BRR juga akan dibangun di lokasi yang sama.
Beberapa toko, warung dan puskesmas desa pun pelan-pelan mulai beroperasi. Plus beroperasinya sekolah tingkat TK milik USAID dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Leupung. Meskipun jumlah murid sangat sedikit. Lantaran jumlah anak usia sekolah yang masih tersisa hanya puluhan orang. Di samping itu, beberapa penduduk pun mulai berbenah dengan membuka usaha di rumah.
Meski keadaan cenderung lebih “tertata” dari pada keadaan sebelum tsunami menerjang, namun keadaan saat ini jauh berbeda. Terutama dengan tidak hadirnya orang-orang terdekat yang menjadi korban gelombang ganas itu. Barunah misalnya. Perempuan yang suaminya meninggal dunia karena tsunami itu sebelumnya tinggal di Meunasah Masjid dengan 89 orang keluarga besar.

Ketika tsunami menerjang, 80 orang keluarga Barunah menjadi korban. “Tinggal sembilan orang yang selamat, hanya saya perempuannya,” kata Barunah yang ketika kejadian itu terjadi sedang tidak berada di Leupung. Kini, Barunah mendiami sendiri rumah baru di Meunasah Masjid. “Biar saya tetap di sini, di tanah milik keluarga saya,” kata Barunah yang kini menjanda.
Meski begitu, Barunah yang juga saudara perempuan dari Samidan, Guechik Meunasah Masjid itu tetap bersyukur. Tetangga rumah yang kebanyakan juga merupakan korban selamat tsunami sudah seperti saudara dekat. “Semua yang ada di sini sudah seperti saudara sendiri, masing-masing saling membantu satu sama lain, alhamdulillah,” katanya.
Keluarga Ja’far pun sama. Laki-laki 42 tahun yang dulu berprofesi sebagai pengemudi labi-labi (angkot) ini adalah salah satu korban selamat tsunami. Istri dan keluarga Ja’far yang lain ikut menjadi korban derasnya gelombang dari laut Samudra Hindia itu. Kini Ja’far melanjutkan hidupnya sebagai sopir truk untuk mengangkut material pembangunan jalan di sekitar Leupung.
Berbeda dengan Barunnah, Ja’far memilih untuk kembali membangun keluarga dengan menikahi Yusnaini. Keduanya tinggal di rumah rekonstruksi yang dibangun Plan Aceh di Meunasah Masjid. “Ya,.. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kami sudah menata kehidupan kami, mungkin ini sudah digariskan dan harus kita jalani,” kata Ja’far.
Plus Minus Rumah BaruBagi keluarga yang tersisa pasca tsunami, hidup di tanah leluhur dengan kondisi yang sama sekali baru, bukanlah hal yang mudah. Perlu adaptasi yang cukup lama untuk bisa memahami semua hal yang “tersaji” di depan mata. “Rumah baru” adalah salah satunya. Puluhan unit rumah yang dibangun di Meunasah Masjid berasal dari beberapa penyandang dana yang berbeda. Dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda pula. Meskipun ukurannya relatif sama, type 36.
“Masing-masing rumah memiliki karakter yang berbeda, tergantung siapa yang membangun,” kata Ja’far. Misalnya rumah milik Plan Aceh-Habitat Humanity. Dari sisi fisik, bangunannya tergolong sama, dengan ruang utama, kamar mandi dan teras depan dan belakang. Hanya saja, Plan Aceh-Habitat menambah tegel keramik sebagai pemanis bagian dalam. Sementara rumah milik ADB mempunyai kerangka atap dari besi baja yang kuat.
Dibandingkan seluruh rumah yang sudah dibangun, rumah milik Muslim Aid dan Oxfam dinilai lebih layak. Meskipun lantai tidak dilapisi keramik, namun Muslim Aid dan Oxfam memberikan fasilitas lain berupa kompas gas plus tabung gasnya, furniture, ranjang dan lemari kayu. BRR pernah membangun rumah di areal yang sama, namun tidak sesuai dengan spek yang diharap masyarakat. Terutama soal pondasi dan dinding dari batako. Karena itu masyarakat menghancurkan bangunan itu. Mereka menginginkan bangunan rumah yang lebih layak.

Bagi keluarga yang baru saja dirundung kesusahan dan kehilangan seluruh harta benda karena tsunami, fasilitas rumah dan furniture yang diberikan oleh Muslim Aid dan Oxfam dianggap paling “masuk akal”. Hal itu yang dikatakan oleh keluarga Anwar dan Salimah. “Kami tidak memiliki apapun setelah tsunami, rumah yang kami dapat juga tidak ada isinya, akhirnya kami harus berpikir untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” kata Anwar yang kini menghuni rumah milik Plan Aceh-Habitat Humanity.
Anwar dan Salimah tidak sendirian. Mereka tinggal bersama dua anak yang masih bayi dan balita. Sasabila, 2, 5 tahun dan Maulana, 7 bulan. Hidup bersama dua anak kecil dalam kondisi rumah memang bukan hal yang mudah. Apalagi rumah milik Plan Aceh-Habitat Humanity tidak dilengkapi pula dengan dapur. Salimah, sang ibu kesulitan untuk menyiapkan makan dan membuat susu untuk dua anaknya. “Terpaksa semua kami lakukan di ruang tamu,” kata Salimah yang ketika tsunami menerjang, 14 keluarganya meninggal dunia atau hilang.
Perihal kebutuhan dapur juga dirasakan oleh keluarga Zafrizal dan Unonen. Keluarga yang memiliki dua anak yang kini bersekolah di TK milik USAID itu terpaksa menambahkan sendiri bagian dapur miliknya dengan papan bekas bangunan yang tidak terpakai. “Dapur memang kebutuhan yang harus ada, maka kami mencoba membuatnya sendiri meski secara sederhana,” kata Zafrizal.
Hasilnya tidak mengecewakan. Dalam sebuah kunjungan ke rumah Zafrizal dan Unonen, sekilas rumah itu memang terlihat tidak rapi lantaran banyak mainan anak-anak yang berserakan. Namun hal itu tetap tidak menghilangkan peran peruntukan tiap ruang. Baju-baju bersih misalnya, tertata di tiap kamar yang ada. Juga peralatan dapur dan cuci baju kotor, semuanya ada di bagian belakang rumah. Begitu juga dengan buku-buku pelajaran anak-anak yang tertata di pojokan ruang tamu.
Masukan menarik datang dari keluarga Ja’far dan Yusnaini. Keluarga ini mepersoalkan jumlah ruangan milik Plan Aceh-Habitat Humanity yang hanya dibagi dalam tiga ruangan. Ruang tamu, satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Sementara, satu kamar lagi hanya disekat dengan menggunakan teriplek kayu. Kondisi ini menyulitkan bagi keluarga yang mempunyai anak baru gede (ABG) yang jelas membutuhkan ruangan pribadi.
Karena alasan itulah, keluarga Ja’far dan Yusnaini memilih untuk tidak menempatkan anak semata wayangnya, Isra ke rumah orang tua Yusnaini di Selimum, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. “Di sana banyak teman dan banyak ruangan yang bisa ditempati, mungkin kalau sudah lulus SD bisa kembali ke Meunasah Masjid,” kata Yusnaini.
Rumah Ja’far dan Yusnaini tergolong unik. Selain tampak rapi dengan furniture yang bagus, rumah itu juga memiliki beberapa bangunan tambahan. Seperti dapur dan ruang cuci baju dan cuci piring di luar rumah bagian belakang. Sementara kebun belakang rumah ditanami dengan ketela pohon. “Ketela pohon itu sengaja kami tanami, selain untuk kami gunakan hasilnya, juga untuk hiasan mata, hijau-hijauan lah,” katanya.
Saluran Pembuangan dan Meunasah
Hal lain yang menjadi problem dalam persoalan rumah di Desa Meunasah Masjid, Kecamatan Leupung adalah tidak adanya saluran pembuangan air kotor. Agaknya, hal ini menjadi persoalan laten yang dikemudian hari akan memunculkan persoalan baru. Dalam pengamatan, hampir semua penghuni perumahan baru di Meunasah Madjid, membuang saluran air kotornya di halaman bagian belakang rumah. Tidak mengherankan bila banyak sekali genangan air kotor atau tanah basah bekas buangan air kotor.
Sekretaris Desa Meunasah Masjid Abdul Jalil menyadari hal itu. Menurut laki-laki yang kini berjualan voucer telepon seluler di rumahnya ini, hal saluran air kotor sudah sering dibicarakan oleh masyarakat sekitar. “Sering sekali kita bicara soal saluran pembuangan itu, mulai got sampai saluran pembuangan dari air cucian piring dan baju, namun sampai sekarang tidak ada solusi soal itu,” katanya.
Masyarakat ingin membangun sendiri saluran itu, namun terbentur dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan. Kalaupun bisa dibuat dengan seadanya, malah khawatir akan mmunculkan problem baru, karena masyarakat tidak mengetahui rencana utuh pembangunan di kawasan itu. “Kami kawatir, kalau saluran itu diserahkan ke masyarakat tanpa kita tahu rencana pembangunannya, akan malah merepotkan,” katanya. “Karena itu, sampai saat ini kami memilih untuk membuangnya di tanah saja,”
Meunasah atau masjid kecil (mushola) juga masih menjadi impian. Biasanya, bagi masyarakat di NAD, keberadaan meunasah adalah bagian yang tidak terpisahkan. Namun di Desa Meunasah Masjid, justru tidak memiliki meunasah. Yang ada hanya meunasah sementara yang terletak di samping Polsek Leupung yang ada di pinggir jalan utama di pinggir desa.
“Mungkin NGO dan BRR lupa mengagendakan pembangunan meunasah di desa Meunasah Masjid, kita sangat membutuhkan meunasah. Masa’ Desa Meunasah Masjid tidak memiliki meunasah?” kata Abdul Jalil. Benar juga ya...